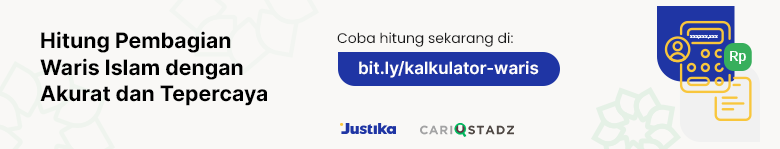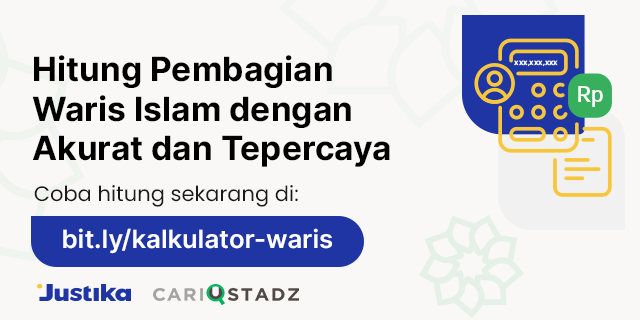Bagaimana al-Qur’an memandang jiwa? Lalu, apakah al-Qur’an juga berbicara tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit mental yang acapkali diderita manusia modern yang penuh dengan tantangan dan godaan ini? Apakah kita bisa mendeteksi penyakit hati atau jiwa? Beberapa penjelasan penulis berikut ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
Jiwa yang sehat perspektif al-Qur’an bukanlah sebuah kondisi psikologis yang bebas dari segala gangguan, akan tetapi keseluruhan kehidupan batin yang melibatkan berbagai unsur seperti nafs, qalb, dan ruh. Al-Qur’an menyebutkan kata nafs dengan beragam makna seperti jiwa, diri, maupun dorongan yang bisa menggerakkan perilaku seseorang. Dorongan itu bisa baik maupun buruk, tergantung kualitas spiritualnya.
Tradisi psikologi Islam klasik seperti yang dirumuskan al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumudddin menjelaskan bahwa hakikat manusia tidak berhenti pada aspek fisik atau lahiriyah semata, melainkan terletak pada dimensi intelektual ruhaninya yang diungkapkan lewat istilah qalb, ruh, dan ‘aql yang saling terkait (Ahmad Rofi’i, Signifikansi Psikologi Islam).
Ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa kajian para ulama’ memetakan jiwa ke dalam beberapa tingkatan. Ada nafs al-ammarah atau jiwa yang mendorong pada kejahatan (Q.S. Yusuf: 53), ada juga nafs al-lawwamah atau jiwa yang amat menyesali dirinya karena berbuat kejahatan (Q.S. al-Qiyamah: 2), ada juga nafs al-muthma’innah atau jiwa yang tenang (QS. al-Fajr :27–30). Sejumlah mufasir seperti al-Qurtubi dan Quraish Shihab misalnya memaknai nafs al-muthma’innah sebagai jiwa seorang mukmin yang percaya akan wujud Allah, ikhlas, taat, membenarkan hari kebangkitan, dan beramal saleh sehingga mencapai ketenangan batin yang stabil (al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi. Qurasih Shihab, al-Misbah). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini selaras dengan konsep resilience, inner peace, dan meaning in life dalam psikologi positif kontemporer (Ernisah, Kesehatan Mental dalam Pendidikan Islam)
Dalam diskursus psikologi Islam modern, sarjana seperti Zakiyah Daradjat menekankan bahwa kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari dimensi keagamaan. Ia melihat keseimbangan spiritual sebagai faktor kunci kesehatan psikologis, khususnya melalui pendidikan iman dan akhlak. Sementara al-Balkhi jauh sebelumnya telah menawarkan pendekatan yang holistik terhadap kesehatan fisik dan jiwa dalam kitab Masalih al-Abdan wa Anfus (Ahmad Teguh, Kesehatan Mental). Al-Balkhi mengidentifikasi gejala kecemasan dan depresi kemudian mengusulkan teknik yang sekarang dikenal dengan terapi kognitif perilaku modern, atau sebuah pendekatan yang difokuskan untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi lebih sehat, membantu mengatasi depresi, rasa cemas, fobia, dsb.
Lebih jauh, kajian psikologi Qur’ani—pendekatan studi untuk memahami jiwa dan perilaku manusia berdasarkan Al-Qur’an—juga menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual seperti sabar, tawakkal, syukur, ikhlas, dsb. juga memiliki efek yang nyata, seperti menenangkan batin dan menurunkan kecemasan (Rahim Kamarul, Kawalan Kesejahteraan Psikologi). Karenanya, di sini penting digaris bawahi bahwa dzikir, maupun solat yang kita lakukan sehari-hari itu sejatinya bukan sekedar ritual belaka, tetapi hal itu merupakan coping spiritual untuk bisa menumbuhkan itmi’nan al-qulub (ketenangan hati) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ra’d: 28,
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ
(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.
Ayat di atas menemukan relevansinya dengan penejelasan Nabi yang sudah menjadi sangat populer, yakni tentang posisi qalb yang begitu sentral. Ia sentral karena disebut Nabi sebagai penentu kesehatan jiwa dan perilaku.
…أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (متفق عليه)
Sesungguhnya dalam diri terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh
tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati.” (HR.
Bukhari dan Muslim)
Sebagaimana penulis utarakan, hadis ini memang populer bagi kalangan muslim, namun penerapannya yang belum tentu populer. Kapankah kita akan mempopulerkan pesan Nabi di atas dalam kehidupan kita? Tentu, kita sendiri yang mampu menjawabnya.
Jiwa yang sehat ala al-Qur’an memang tidak cukup dengan mendakwakan diri bebas dari gangguan mental saja. Lebih dari itu, jiwa seorang muslim yang sehat adalah jiwa yang bertauhid, tenang, bersih dari penyakit hati, berakhlak mulia, dan tetap menghormati sesama manusia. Fitrah manusia yang cenderung akan kebaikan sebenarnya selalu mendambakan ketentraman, namun pengalaman dan cobaan kehidupannya kadang membawanya menuju jalan yang gelap. Di sinilah peran al-Qur’an dalam membimbing jiwa manusia agar tidak terpuruk dalam kegelapan itu.
Zaimul Asroor. M.A., Dosen IAI Khozinatul Ulum Blora dan Ustadz di Cariustadz.id
Tertarik mengundang ustadz Zaimul Asroor. M.A.? Silahkan klik disini