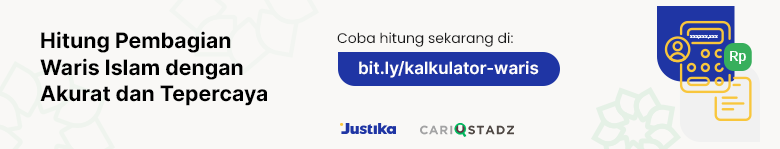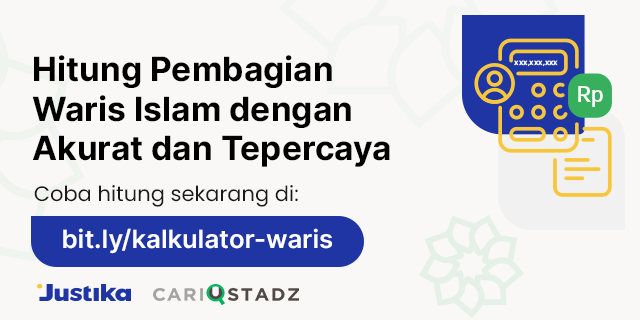Kita semua tentu akrab dengan kisah-kisah dalam Al-Qur’an. Dari kecil, telinga kita sudah sering mendengar cerita tentang Fir’aun yang congkak, Qarun yang tamak, atau Musa yang tegas memperjuangkan kebenaran. Tetapi, sering kali kita memperlakukan kisah itu tidak lebih hanya sekadar dongeng masa lalu—catatan sejarah yang jauh dari kehidupan kita hari ini. Padahal, Al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa kisah-kisah itu diturunkan bukan untuk dikenang, melainkan untuk direnungkan.
Allah berfirman: “Sungguh, pada kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (QS. Yusuf: 111). Artinya, dalam kisah tersebut ada pola universal yang terus berulang dalam setiap zaman. Tokoh-tokoh dalam Qur’an tidak berhenti di masa lampau, melainkan hadir di masa kini dalam bentuk peran sebagai arketip yang hidup dan terus diperankan manusia hingga kini.
Kalau kita membaca Al-Qur’an dengan kacamata harfiah semata, tokoh-tokoh di dalamnya akan tampak seperti sekadar catatan sejarah masa lalu. Nama-nama besar seperti Fir’aun, misalnya, seakan berhenti pada kisah faktual. Padahal, sebagaimana pernah digarisbawahi Abbas al-‘Aqqad, Al-Qur’an bukanlah kitab kronik sejarah, melainkan kitab arketip—kitab yang menyimpan pola-pola universal tentang manusia dan peradaban.
Tatkala Qur’an menghadirkan tokoh seperti Fir’aun, pesan utamanya tidak semata menceritakan seorang raja Mesir kuno, tetapi memperlihatkan wajah tirani yang bisa lahir di mana saja. Ia merupakan simbol kekuasaan yang melampaui batas (abuse of power), menolak kebenaran, dan menindas mereka yang lemah.
Maka, setiap kali kita melihat seseorang atau siapapun dengan perilaku semacam itu, yang anti-kritik, represif, atau memanipulasi hukum atau peraturan demi kepentingan pribadi, di situlah kita sesungguhnya tengah berhadapan dengan “Fir’aun” yang hidup pada zaman kita.
Fir‘aun Lebih dari Sekadar Tokoh, Ia Adalah Peran yang Selalu Hadir
Dalam Surah Yunus ayat 90, Al-Qur’an mengisahkan momen genting ketika Fir‘aun hampir tenggelam dan tiba-tiba menyatakan keimanannya. Ini menarik dari sisi sejarah, karena seseorang akan berubah pikiran tatkala dalam kondisi terdesak. Qur’an seakan berbicara kepada kita bahwa pola ini akan selalu berulang dalam lintasan kehidupan manusia kapanpun dan di manapun.
وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۗحَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَاۤءِيْلَ وَاَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
Kami jadikan Bani Israil bisa melintasi laut itu (Laut Merah). Lalu, Fir‘aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir‘aun hampir (mati) tenggelam, dia berkata, “Aku percaya bahwa tidak ada tuhan selain (Tuhan) yang telah dipercayai oleh Bani Israil dan aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri kepada-Nya).” (Q.S. Yunus [10]: 90)
Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib mengajukan pertanyaan kritis terkait tafsir ayat di atas: bagaimana mungkin seseorang yang sedang sekarat dan tenggelam mampu melafalkan kata-kata tersebut? Jawaban yang ia berikan cukup menarik.
Pertama, yang dimaksud ucapan dalam ayat itu, menurut Ar-Razi, bukanlah kata-kata lisan, melainkan bisikan jiwa. Artinya, Fir‘aun tidak benar-benar mengucapkannya dengan lidah, melainkan sekadar lintasan hati. Hal ini sekaligus menjadi dalil bahwa “ucapan jiwa” juga dapat dicatat sebagai pernyataan, meski tidak terartikulasikan secara verbal.
Kedua, terkait dengan waktu dan bentuk pengakuan Fir‘aun. Ia disebutkan tiga kali mengaku beriman: pertama, “Aku beriman”; kedua, “Tidak ada Tuhan selain Dia yang dipercayai Bani Israil”; dan ketiga, “Aku termasuk orang-orang Muslim.” Lalu muncul pertanyaan: mengapa Allah tidak menerima keimanannya? Al-Razi menjawab dengan beberapa penjelasan.
Pertama, iman yang datang pada saat azab sudah menimpa tidak pernah diterima, sebab itu lahir dari kepanikan, bukan dari kesadaran. Al-Qur’an sendiri menegaskan, “Maka iman mereka tidaklah bermanfaat ketika mereka telah melihat azab Kami” (QS. Ghafir: 85). Kedua, pengakuan Fir‘aun tidak didasari ketulusan, melainkan sekadar strategi “bersilat lidah” guna menyelamatkan (atau mengamankan) diri dari musibah. Ia tidak sungguh-sungguh mengakui keagungan Allah dan kehinaan dirinya sebagai hamba, melainkan hanya mencari jalan keluar dari penderitaan.
Ketiga, keimanannya bersifat imitasi. Ia berkata, “Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diyakini Bani Israil”—seolah menegaskan bahwa ia tidak mengenal Allah kecuali melalui kabar yang ia dengar dari Bani Israil. Ini menunjukkan kelemahan iman yang tidak lahir dari penghayatan, melainkan sekadar tiruan.
Tidak jauh berbeda dengan Ar-Razi, Al-Biqa‘i dalam Nadzm ad-Durar menjelaskan bahwa kisah penyeberangan Bani Israil bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi menggambarkan bagaimana kesabaran yang lahir dari pengetahuan selalu berbuah keselamatan. Allah menegaskan, “Dan Kami seberangkan Bani Israil melintasi laut”— di sini tampak bahwa Allah tidak hanya memberi izin, tetapi benar-benar menyertai mereka dalam perjalanan itu. Kata “bersama Bani Israil” menunjukkan bahwa Allah meridhai langkah mereka, membimbing mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan.
Namun, di balik keselamatan itu, tersimpan juga kebinasaan bagi Fir‘aun dan bala tentaranya. Mereka mengejar Bani Israil bukan karena kebenaran, melainkan karena kedengkian, kesombongan, dan permusuhan. Fir‘aun tak mampu melepaskan egonya sebagai penguasa tiranik; ia merasa harga dirinya jatuh bila membiarkan Musa dan kaumnya merdeka.
Maka, ia memaksa diri dan pasukannya untuk terus mengejar, padahal yang ia lawan sesungguhnya bukan sekadar Musa, melainkan keputusan Ilahi. Al-Biqa‘i menyebutnya sebagai bentuk baghy (penindasan) dan ‘udwan (permusuhan)—dua sifat yang mempercepat kehancuran siapa pun yang menempuhnya.
Dari sini, kita melihat betapa Fir‘aun menjadi simbol penguasa tiranik yang baru tersadar ketika ajal menjemput. Namun, kesadaran yang datang terlambat tidak mampu menyelamatkannya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita: jangan sampai kita menunggu bencana atau kesempitan hidup baru kemudian mengaku beriman. Karena iman yang lahir dari keterpaksaan, tanpa ketulusan dan penghayatan, tidak pernah diterima.
Jika sebelumnya kita menyebut Fir‘aun sebagai arketip kekuasaan tiranik yang bisa hadir kapan saja, maka tulisan ini menegaskan sisi lain: Fir‘aun juga mencerminkan watak manusia yang keras kepala, menolak kebenaran saat diberi kesempatan, lalu berpura-pura tunduk hanya ketika tak lagi punya pilihan (bermuka dua).
Dalam realitas kehidupan modern, sikap seperti ini bisa kita jumpai pada diri kita masing-masing. Atau bagi mereka yang baru “bertaubat” ketika tertangkap basah, baru menyesali perbuatan ketika terjerat skandal, atau baru mengaku salah ketika jabatan dan kekuasaannya runtuh. Dengan kata lain, Fir‘aun bukan hanya kisah masa lalu, tetapi cermin bagi siapa pun yang menunda iman hingga terlambat.
Senata Adi Prasetia, M.Pd, Ustadz di Cariustadz
Tertarik mengundang ustadz Senata Adi Prasetia, M.Pd? Silahkan klik disini