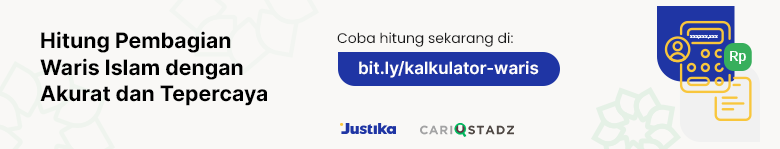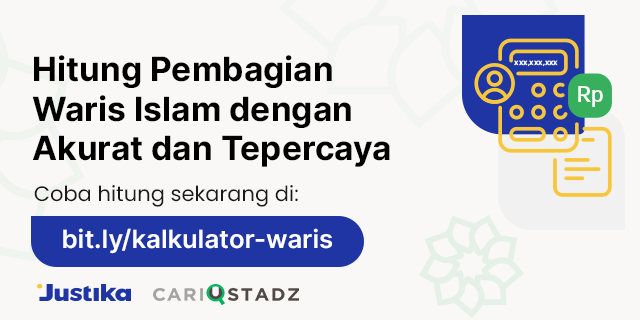Dalam menghadapi problematika dunia yang semakin tidak menentu, Al-Qur’an memberikan panduan kepada kita agar tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Sebab, dengan optimis, kita akan lebih semangat dalam menjalani hidup. Dengan optimis pula, kita akan melihat sisi positif dunia ini dan hubungan sosial dengan orang lain. Karena agama Islam diturunkan bagi mereka yang memiliki harapan.
Karena itu, Al-Qur’an hadir sebagai pelita yang memandu kita sebagai Muslim agar memiliki ketenangan jiwa, tidak putus asa dan semangat dalam menjalani hidup. Salah satu ayat yang menyimpan kekuatan dahsyat dalam memandu kehidupan ini ialah Surah Ali Imran ayat 134. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tiga karakter utama yang menjadi kunci untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna yakni memberi di kala lapang dan sempit, mengelola amarah, dan memaafkan sesama. Tiga panduan ini bukan sekadar ajaran moral, melainkan resep hidup yang mampu menyehatkan batin dan memperkuat relasi sosial.
Berkontribusi
Pertama, hendaknya hubungan sosial kita dengan orang lain adalah hubungan yang berkontribusi. Sebab dengan berkontribusi akan membuka pintu kemudahan dan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam Surah Ali Imran ayat 134,
الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّۤاءِ وَالضَّرَّۤاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَۚ
(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Ali Imran [3]: 134)
Ayat ini menekankan hendaknya kita selalu berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Artinya, semangat memberi atau berkontribusi tidak hanya muncul tatkala kita memiliki rezeki yang melimpah, tapi justru diuji ketika kita tengah kekurangan.
Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa salah satu ciri utama orang bertakwa adalah kebiasaan menafkahkan harta di jalan Allah, kebiasaan berkontribusi dalam hubungan sosial, tak peduli apakah kita sedang berada dalam kelapangan rezeki atau justru sedang sempit. Memberi di tengah keterbatasan menunjukkan ketulusan hati dan keberanian kita dalam melepas ego.
Senada dengan itu, Al-Baghawi dalam Ma’alim al-Tanzil menegaskan bahwa kedermawanan adalah jalan utama menuju surga. Ia bahkan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW,
السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ
Dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang kikir”.
Dari sini kita belajar bahwa kontribusi bukan sekadar urusan materi, tapi juga soal sikap hidup—tentang keikhlasan memberi dan keberanian peduli, bahkan tatkala diri sendiri tengah kekurangan. Sebab, lewat berkontribusi itulah, kita menyembuhkan ego, menyambung kebaikan, dan mendekatkan diri kepada-Nya.
Mengelola Emosi
Panduan hidup yang kedua adalah bagaimana kita mampu mengelola emosi atau amarah dengan baik (wal kadziminal ghaidz). Sebab, dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa menghindari konflik, gesekan atau perlakuan yang menyakitkan hati. Namun, di situlah ujian sebenarnya: bukan pada apa yang orang lain lakukan, melainkan bagaimana kita meresponsnya.
Dalam konteks menghadapi kesalahan orang lain, sebagaimana penafsiran Shihab, ayat ini menunjukkan tiga kelas manusia atau jenjang sikapnya. Tingkatan pertama ialah mereka yang mampu menahan amarah. Kata al-kāẓimīn menggambarkan seseorang yang menampung kemarahannya seolah-olah air dalam bejana yang sudah penuh, lalu ditutup rapat agar tidak meluap. Artinya, kemarahan itu masih ada, perasaan tidak nyaman masih menggelayuti hati, bahkan pikiran mungkin masih ingin membalas. Namun, ia memilih untuk tidak mengikuti dorongan itu.
Sikap ini bukan tentang menjadi manusia yang tidak punya rasa marah, melainkan tentang menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri di tengah badai emosi. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, orang semacam itu lebih memilih untuk diam, tidak melontarkan kata-kata kasar, tidak melakukan tindakan yang menyakitkan, dan tidak memperkeruh keadaan. Menahan amarah merupakan bentuk kematangan sosial—karena ia bukan hanya menyelamatkan hubungan dengan orang lain, tapi juga menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri.
Al-Baghawi mengutip hadis Nabi SAW,
مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ
“Barangsiapa yang mampu menahan amarahnya padahal ia masih mampu melakukannya, Allah akan memanggilnya pada Hari Kiamat di hadapan seluruh makhluk dan akan mengizinkannya memilih bidadari surga mana pun yang ia inginkan” (HR. Abu Dawud)
Mengutip istilah Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, idza sakata ‘alaihi wa lam yudzhirhu la biqaulin wa la bifi’lin, orang yang mampu mengelola emosi adalah mereka yang memilih diam—tidak membalas dengan kata-kata maupun tindakan. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang luar biasa.
Dalam istilah Islam, perilaku semacam ini dikenal dengan imsak—menahan. Seperti halnya puasa, menahan amarah juga bentuk shaum—menahan diri dari ledakan emosi, dendam, atau keinginan membalas. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah kedermawanan, sifat yang ditonjolkan Al-Qur’an dalam ayat tersebut ialah kemampuan mengelola amarah dan memaafkan.
Bahkan, yang lebih mulia lagi adalah tatkala seseorang tak hanya memaafkan, tapi juga membalas dengan kebaikan. Inilah bentuk ihsan yang paling luhur—karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya.
Dalam konteks sosial, kemampuan semacam ini sangat menentukan kualitas hubungan antarindividu. Masyarakat yang dipenuhi orang-orang yang bisa mengelola emosinya adalah masyarakat yang tentram, tenang dan penuh kedamaian—tempat di mana kebaikan tumbuh dan luka sosial bisa sembuh.
Memaafkan
Panduan hidup ketiga yang diajarkan dalam Surah Ali Imran ayat 134 adalah memaafkan kesalahan orang lain—wal ‘āfīna ‘ani-n-nās. Dalam kehidupan sosial, memaafkan merupakan langkah spiritual sekaligus sosial yang paling menenangkan hati. Ia tidak hanya mendamaikan hubungan dengan orang lain, tetapi juga menyembuhkan luka batin kita sendiri.
Mereka yang mampu memaafkan umumnya memiliki jiwa yang lebih sehat dibanding mereka yang memendam dendam. Dan inilah yang diteladankan Nabi Muhammad ﷺ dalam momen paling menyakitkan: ketika pasukan Muslim berguguran dalam Perang Uhud, sebagian ingin membalas, namun Nabi justru mengajarkan untuk memaafkan.
Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata al-‘āfīna berasal dari kata ‘afn yang berarti “menghapus”. Maka, memaafkan dalam Islam bukan hanya sekadar berkata “saya memaafkan”, melainkan benar-benar menghapus luka itu dari hati, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Jika sebelumnya seseorang hanya sampai pada tahap menahan amarah, maka pada tahap ini ia telah melampaui itu—ia telah menghapus jejak-jejak luka yang ditinggalkan oleh kesalahan orang lain.
Namun, Quraish juga mengingatkan bahwa bisa jadi pada tahap ini, hubungan tidak langsung kembali terjalin karena luka telah hilang, tapi tidak ada dorongan untuk membangun kembali kedekatan. Maka, Allah menutup ayat ini dengan menyebut bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan (wallahu yuhibbul muḥsinīn)—yakni mereka yang bukan hanya menahan amarah dan memaafkan, tapi juga mampu berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti.
Ar-Razi dalam Tafsir al-Kabīr memperkuat makna ini dengan mengutip sabda Nabi ﷺ:
قالَ ﷺ: لا يَكُونُ العَبْدُ ذا فَضْلٍ حَتّى يَصِلَ مَن قَطَعَهُ، ويَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، ويُعْطِيَ مَن حَرَمَهُ ورُوِيَ عَنْ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَيْسَ الإحْسانُ أنْ تُحْسِنَ إلى مَن أحْسَنَ إلَيْكَ، ذَلِكَ مُكافَأةٌ، إنَّما الإحْسانُ أنْ تُحْسِنَ إلى مَن أساءَ إلَيْكَ
“Seorang hamba tidak akan menjadi mulia hingga ia menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan, memaafkan orang yang menzaliminya, dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya.” Bahkan, Isa bin Maryam as. juga berkata: “Kebaikan itu bukan membalas kebaikan orang lain; itu hanya bentuk timbal balik. Kebaikan sejati adalah berbuat baik kepada orang yang menyakitimu.”
Inilah puncak dari etika sosial dalam Islam: mampu mengelola emosi atau amarah, memaafkan, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Sebuah jalan sunyi yang tak mudah, tapi membuka ruang bagi kedamaian yang sejati.
Senata Adi Prasetia, M.Pd, Ustadz di Cariustadz
Tertarik mengundang ustadz Senata Adi Prasetia, M.Pd? Silahkan klik disini