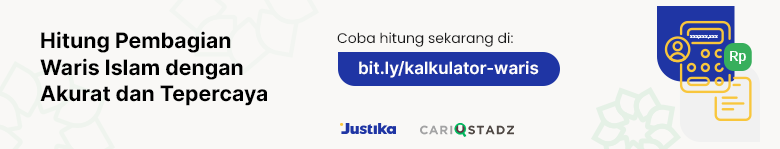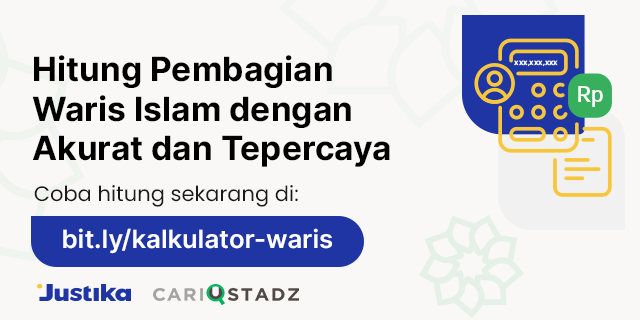Di tengah gempuran era digital dan informasi tiada batas, Indonesia masih menghadapi satu persoalan klasik yang tak kunjung usai yakni rendahnya tingkat literasi. Menurut PISA (Programme for International Student Assessment) terbaru menunjukkan skor literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia berada di bawah rata-rata global dan termasuk yang terendah di ASEAN. Indeks literasi Indonesia masih berada di peringkat bawah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Rendahnya literasi ini bukan sekadar persoalan kurangnya minat baca, tetapi lebih jauh: minimnya daya nalar, lemahnya kemampuan berpikir kritis, dan menjamurnya budaya instan dalam menyerap informasi. Padahal, dalam Islam, literasi tidak hanya sekadar keterampilan membaca, tetapi mencakup kemampuan memahami, mengolah, dan mengambil hikmah dari pengetahuan.
Bahkan, Alquran sebagai kitab suci umat Islam membuka wahyu pertamanya dengan perintah literatif: Iqra’ — bacalah! Artikel ini akan mengeksplorasi tiga makna literasi dalam Alquran yang bisa menjadi pondasi kebudayaan berpikir umat Islam sekaligus menjadi solusi spiritual dan intelektual atas rendahnya daya nalar bangsa.
Iqra’: Jalan Menuju Peradaban Ilmu
Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi:
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! (Q.S. Al-‘Alaq [96]: 1)
Kata iqra’ secara harfiah berarti bacalah. Dalam berbagai kamus, seperti yang dijelaskan Quraish Shihab, ditemukan berangeka ragam arti dari kata tersebut, antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu dan sebagainya, yang ke semuanya bermuara pada arti menghimpun.
Namun dalam konteks wahyu, bacaan yang dimaksud bukan hanya sekadar mengeja huruf atau mengenali teks, melainkan proses internalisasi pengetahuan dengan menyertakan kesadaran spiritual (bismi rabbik — dengan nama Tuhanmu). Artinya, literasi pertama dalam Al-Qur’an merupakan literasi spiritual-intelektual sekaligus intelektual-transendental yaitu kemampuan membaca dengan menyambungkan akal dengan wahyu, antara fakta dan makna, antara teks dan konteks.
Menurut Al-Biqa’i dalam Nadzm Al-Durar, kata iq’ra lebih dari sekadar membaca, melainkan menghimpun sesuatu yang lebih agung (al-jam’u al-a’dzam). Sementara, Muhammad ‘Abduh, sebagaimana dikutip Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, mengungkapkan makna perintah membaca di sini bukan sebagai beban tugas yang harus dilaksanakan (amr taklifi) sehingga membutuhkan objek, melainkan ia adalah amr takwini yang mewujudkan kemampuan membaca secara aktual pada diri pribadi Nabi Muhammad saw.
Jadi, iqra’ atau perintah literasi di sini bukanlah aktivitas mekanis, melainkan proses yang lebih besar dari itu yakni proses pemanusiaan. Seorang Muslim diperintahkan untuk menjadi pembaca kehidupan, bukan sekadar pembaca huruf. Di sinilah literasi menjadi sarana menuju ‘ilm (pengetahuan), yang merupakan pondasi utama kemuliaan manusia.
Tadabbur: Literasi yang Bermakna
Al-Qur’an tidak memandang aktivitas membaca sebagai tindakan sekadar melafalkan huruf dan mengeja kata. Lebih dari itu, membaca dalam pandangan Al-Qur’an menuntut perenungan yang mendalam dan keterlibatan hati. Dalam Surah Muhammad ayat 24, Allah menegur dengan pertanyaan retoris:
اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا
Tidakkah mereka merenungkan (menghayati) Al-Qur’an? Ataukah hati mereka telah terkunci? (Q.S. Muhammad [47]: 24)
Ayat ini mengandung kritik tajam terhadap mereka yang membaca tanpa merenung, mengahayati, memahami tanpa menggali makna, dan mendengar tanpa membuka hati. Tafsir klasik yang disampaikan Imam At-Tabari dalam Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān memperjelas makna ayat ini. Menurutnya, Allah sedang menegur kaum munafik yang tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Padahal, melalui firman-Nya, Allah telah menjelaskan berbagai dalil yang seharusnya membuka mata dan hati mereka terhadap kesesatan jalan yang selama ini mereka ikuti.
Dengan kata lain, membaca Al-Qur’an tanpa tadabbur—tanpa perenungan dan keterlibatan akal-budi—sama saja dengan membiarkan hati tetap terkunci. Tadabbur menuntut lebih dari sekadar membaca; ia menuntut pembacaan yang menggugah kesadaran, membentuk nalar, dan menghidupkan hati.
Tadabbur, dalam hal ini, merupakan bentuk literasi tingkat lanjut: literasi kritis-reflektif. Ia mengajak pembaca untuk berpikir mendalam, menggali makna di balik teks, dan menghubungkannya dengan realitas sosial. Dalam dunia pendidikan modern, ini setara dengan critical thinking — kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi informasi yang berseliweran tanpa verifikasi. Jika dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran deep learning, tadabbur bisa disepadankan dengan mindful learning: pembelajaran yang bermakna dan substantif.
Dalam konteks Indonesia, budaya tadabbur ini bisa menjadi solusi atas rendahnya nalar kritis masyarakat. Banyak yang membaca Al-Qur’an atau teks lainnya, tetapi tidak memikirkan maknanya atau mengkajinya secara mendalam. Akibatnya, mudah terjebak dalam berita bohong (hoax), teori konspirasi, hingga tafsir keagamaan yang ekstrem.
Tafakkur: Literasi sebagai Renungan atas Tanda-Tanda Tuhan
Al-Qur’an secara konsisten mendorong manusia untuk menggunakan akalnya—tidak hanya untuk memahami ajaran agama, melainkan juga untuk merenungi keajaiban semesta. Salah satu seruannya yang terkenal terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 191:
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. (Q.S. Ali Imran [3]: 191)
Ayat ini menunjukkan bahwa berpikir (tafakkur) merupakan bagian penting dari ibadah seorang Muslim. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memperlihatkan adanya dua bentuk pendekatan terhadap realitas: dzikir dan pikir. Dzikir, menurut beliau, berorientasi pada pengenalan terhadap Allah, yang ruangnya lebih banyak melibatkan dimensi hati dan rasa. Sementara itu, tafakkur atau berpikir lebih diarahkan pada penciptaan dan fenomena alam, yaitu makhluk-makhluk ciptaan-Nya.
Akal manusia diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyelami misteri ciptaan—langit, bumi, dan seluruh dinamika kehidupan. Namun, kebebasan itu memiliki batas tatkala menyentuh hakikat Dzat Allah. Dalam hal ini, Quraish Shihab mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim melalui Ibn ‘Abbas: “Berpikirlah tentang makhluk Allah, dan jangan berpikir tentang Allah”
Artinya, Al-Qur’an menempatkan akal pada posisi yang mulia, namun tetap proporsional. Tafakkur menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan keimanan—di mana manusia merenungi alam semesta bukan sekadar untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai jalan menuju kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta.
Ini disebakan karena kehadiran Allah dan keyakinan akan keesaan-Nya adalah fitrah yang menyertai jiwa manusia. Fitrah, lanjut Shihab, itu tidak dapat dipisahkan dari manusia, paling hanya tingkatnya yang berbeda, sekali atau pada seseorang, ia sedemikian kuat, terang cahayanya melebihi sinar mentari.
Tafakkur, dalam hal ini, merupakan bentuk literasi eksistensial. Tidak hanya berpikir, tetapi juga merenungi. Ia menuntut ketenangan batin, kedalaman spiritual, dan keberanian intelektual untuk melihat keteraturan dan makna dalam kehidupan. Ini adalah literasi kosmik dan kontemplatif — membaca alam semesta sebagai kitab Tuhan yang terbentang.
Dalam masyarakat modern yang serba cepat dan instan, kemampuan tafakkur semakin langka. Padahal, inilah jenis literasi yang mengantarkan seseorang pada kebijaksanaan dan keutuhan jiwa. Tafakkur menanamkan kesadaran ekologis, sosial, dan spiritual, jauh melampaui sekadar teknis membaca.
Jadi, tiga bentuk literasi dalam Alquran — iqra’, tadabbur, dan tafakkur — menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi pembaca aktif, kritis, dan reflektif. Literasi tidak hanya semata keterampilan kognitif, melainkan jalan menuju peradaban, keimanan, dan kebijaksanaan. Sudah saatnya umat Islam, khususnya di Indonesia, membangun budaya literasi yang tidak hanya terfokus pada kecepatan informasi, tetapi juga pada kedalaman makna. Karena hanya dengan literasi yang berakar pada nilai-nilai Qurani, kita bisa membangun masyarakat yang berpikir kritis, berperilaku bijak, dan beriman cerdas.
Senata Adi Prasetia, M.Pd, Ustadz di Cariustadz
Tertarik mengundang ustadz Senata Adi Prasetia, M.Pd? Silahkan klik disini